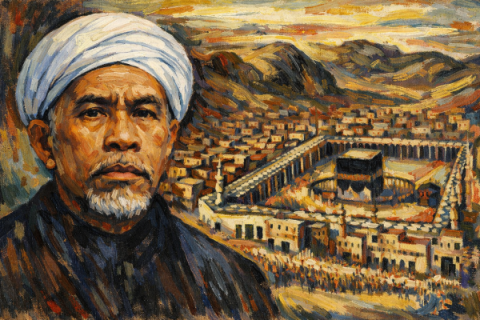Wartatrans.com, ACEH — Bencana di Aceh nyaris tak pernah memberi aba-aba. Ia datang tiba-tiba, merobohkan rumah, merusak ladang, dan meninggalkan jejak panjang penderitaan. Namun ada ruang lain yang kerap luput dari perhatian: dapur para seniman, kesehatan mereka, serta keberlanjutan hidup yang makin rapuh setelah bencana berlalu.
Dari kondisi itulah lahir sebuah ikhtiar yang oleh para seniman Aceh disebut cabe jadi beras. Sebuah metafora sederhana tentang bertahan hidup dengan apa yang tersedia, tentang seni yang tidak melayang di awang-awang, tetapi turun ke tanah—menyentuh kebutuhan paling dasar manusia.

Setidaknya terdapat 14 kabupaten dan kota di Aceh tempat seniman terdampak langsung oleh bencana. Angka itu besar. Sementara daya yang dimiliki komunitas seni sangat terbatas. Tidak semua dapat dijangkau. Fakta ini tidak ditutupi, justru dirawat sebagai pengingat bahwa kerja kemanusiaan selalu berjalan dalam keterbatasan.
“Secara manusiawi kami lemah, langkah kami pendek, dan daya kami tak sebanding dengan luasnya luka,” kata seorang penggerak solidaritas. Namun, mereka percaya bahwa setiap gerak kecil yang tulus selalu menyimpan makna yang lebih besar. Ketika satu karung beras berpindah bahu, ketika seorang seniman menolong seniman lain, di situlah ikhtiar manusia bersentuhan dengan kerja Ilahi.
Dalam kerja yang sunyi itu, Ketua Dewan Kesenian Aceh (DKA), Dr. Afifuddin, tidak hadir sebagai simbol jabatan. Ia turun langsung ke lapangan, ikut memanggul, menyalurkan, dan merasakan beratnya beban. Kehadirannya menegaskan bahwa solidaritas tidak lahir dari meja rapat, melainkan dari keberanian berbagi nasib.
Seluruh donasi yang disalurkan berasal dari kerja halal dan semangat gotong royong—dari sesama seniman, akademisi, dan masyarakat, baik dari Aceh maupun luar negeri. Hingga kini, para penggerak solidaritas mencatat satu hal dengan jujur: belum ada bantuan yang datang dari pemerintah.
Di titik inilah pertanyaan itu muncul, pelan namun tak terelakkan: di mana negara?
Pertanyaan tersebut tidak disampaikan dengan teriakan atau kemarahan. Ia hanya dicatat sebagai kehadiran yang belum terasa—di dapur-dapur yang padam, di tengah seniman yang terus berkarya sambil menahan lapar dan cemas. Barangkali negara sedang dalam perjalanan, atau sibuk di tempat lain. Namun bagi mereka yang terdampak, waktu tidak pernah bisa ditunda.
Sebagai lembaga resmi, Dewan Kesenian Aceh telah dua kali menyurati Menteri Kebudayaan. Hingga tulisan ini disusun, tak satu pun surat memperoleh jawaban. Karena itu, mereka memilih untuk tidak mengirim surat ketiga.
“Sebagai ikhtiar lembaga, kami sudah dua kali menyurati Menteri Kebudayaan dan belum satu pun mendapat jawaban. Karena itu kami tidak akan menyurati untuk yang ketiga kalinya. Bencana tidak menunggu balasan surat, dan seniman tidak bisa hidup dari rapat ke rapat. Maka kami memilih terus berjalan—bekerja dengan apa yang ada, sebagai amanah,” ujar Dr. Afifuddin.
Para penggerak ini sadar sepenuhnya bahwa mereka bekerja untuk kelompok yang sejak lama berada di pinggiran. Seni kerap dipanggil saat panggung terang, tetapi dilupakan ketika bencana datang. Seniman diminta menyuarakan luka kolektif, namun sering dibiarkan sendiri ketika luka itu menjelma kebutuhan paling mendasar.
Karena itu mereka memilih bekerja dalam senyap. Tidak menunggu sorot, tidak menagih pujian. Dengan seni mereka berbagi, dengan empati mereka saling menguatkan. Cabe bisa menjadi beras, karya bisa menjadi penghidupan, dan solidaritas menjelma jaring pengaman paling awal ketika negara belum tiba.
Ikhtiar ini akan terus berjalan—perlahan, terbatas, namun teguh. Hingga rapa’i kembali bergemuruh, hingga bantal didong ditepuk bukan oleh tangan yang gemetar karena lapar, melainkan oleh tangan yang merayakan kehidupan. Pada saat itulah cabe jadi beras tak lagi sekadar metafora, melainkan bukti bahwa solidaritas seniman Aceh benar-benar hidup.*** (LK. Ara)